Renungan Sang Politisi Gaek.ET TU, JOKO!?
Smith Alhadar/Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
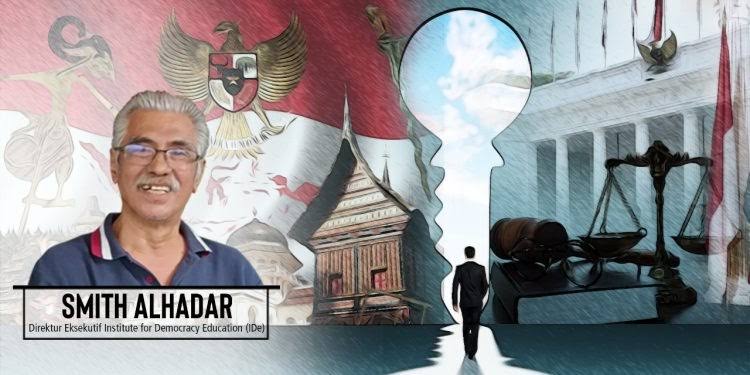
Aku tak bisa tidur. Masalah kenegaraan datang silih berganti tanpa aku memahami substansinya. Di taman belakang rumah aku duduk sendirian di malam yang kian larut. Kutatap aneka kembang warna-warni di bawah siraman cahaya neon, yang nampak seperti perempuan-perempuan muda sedang merayakan kehidupan.
Tapi aku telah kehilangan perasaan untuk menghargai kehadiran mereka. Baru belakangan ini aku merasa hidup hanyalah kekosongan. Bahkan sangat pahit. Bak si miskin mengigau menang lotrei hanya untuk dibangunkan oleh realitas yang getir.
Terdengar lolongan anjing yang mengiris hati, yang seperti memperingatkan adanya bahaya. Sungguh, aku lelah lahir batin. Lelaki ringkih itu, yang masih kuremehkan sampai sekarang, ternyata mampu juga mempermainkan aku.
Aku tak bisa terima petugas partai merongrong wibawaku. Kalau begini bagaimana mungkin aku bisa bangga menjadi putri proklamator yang masyhur itu? Tadi kucopot potret si ringkih-dungu itu dari dinding dan aku banting keras-keras ke lantai. Tak layak kau berada di sini!
Gara-gara dia orang menertawai klaimku bahwa aku tokoh “kharismatik” dan “pintar”. Si ringkih harus aku kalahkan biar pulih wibawaku. Tapi bagaimana caranya? Orang-orang partai lebih mendengarkan dia dari pada aku. Sialan!
Ini menyempitkan ruang manuverku untuk menarik parpol lain bergabung dengan partaiku. Namun, nyaris tak ada yang berminat. Ini pasti karena ancaman si ringkih bedebah itu. Aduh, capres yang aku usung terancam kalah. Meskipun pahit harus aku terima realitas bahwa dialah yang mengendalikan permainan ini.
Sebenarnya semua urusan akan mudah kalau aku sowan kepadanya dan memohon agar dia tak menghancurkan partaiku, yang dulu berjasa besar membawanya ke Istana. Pasalnya, kalau capresku kalah, partaiku ikut merana. Mungkin juga binasa untuk selamanya.
Toh, hampir sampai waktuku. Mungkin ini pilpres terakhirku. Sementara, tak ada penerus yang bisa diandalkan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup partaiku, partai yang aku niatkan untuk menghidup-hidupkan ayahku — sorry, bukab untuk wong cilik — biar seluruh dunia tahu bahwa ayahku tak pernah “mati”.
Tak ada pilihan lain kecuali aku harus mengemis dan memberi konsesi kepada si ringkih-tolol yang dulu aku hina demi membuka kemungkinan ia berbalik mendukung capresku. Tapi gengsiku terlalu besar untuk mengalah kepada orang yang aku anggap tak punya kelebihan apapun kecuali pencitraan yang membuat kewarasan bangsa terganggu.
Aku juga salah: merampas bakal capresku dari tangannya. Aku mengira dengan tindakan itu ia akan kehilangan pengaruh dalam mengutak-atik pilpres. Bola akan berada di kakiku. Dan akulah yang akan menentukan nasibnya pasca lengser kalau capresku menang.
Karena banyak masalah yang akan dia tinggalkan, aku ingin melihat dia seperti kucing basah di depanku. Capresku tokoh populer sehingga aku berharap oligarki dan parpol lain akan antri untuk bergabung dengan koalisi yang dibangun partaiku.
Nyatanya dia tak sedungu yang aku kira. Setidaknya dalam karakter jahat sebagai manusia yang ambisius. Si ringkih tak bisa menerima tindakanku. Dia, dengan wajah ketakutan, melawan dengan bermain teka-teki tokoh yang didukungnya. Bukan hanya publik, aku juga pusing menerka-nerkanya.
Itu cara dia menekanku untuk meningkatkan kartu tawarnya. Dia ingin capresku di bawah pengaruhnya juga. Kurang ajar! Dia mendikteku. Ternyata mampu juga dia memainkan kekuasaan. Bukan hanya itu. Ia juga mengungkap korupsi di kementerian yang disebut-sebut melibatkan partaiku. Bahkan juga menantuku.
Sekarang aku harus bgm? Kalau pura-pura tidaj tahu, bisa jadi ia akan membongkar lebih banyak korupsi yang menyeret pengurus teras partaiku, yang di didalamnya ada putriku juga.
Malah kini dia maju lebih jauh dengan memerintahkan penegak hukum menggeledah kantor menteri dari partaiku. Kali ini aku perintahkan fraksi partaiku di parlemen untuk menjegal kebijakannya. Masih banyak kartu lain yang bisa aku mainkan untuk menekannya.
Tapu dia orang yang tega dan konyol. Bisa hancur bangsa ini bila kami kuat-kuatan dalam berebut hegemoni. Ia memegang rahasia kejahatan kader dan orang-orang ku di banyak institusi, yang bila dibongkar akan keos negeri ini, akan melumatkan partaiku.
Baru sadar aku sekarang bahwa petugas partaiku itu adalah seekor harimau luka, bukan kucing. Dia sedang menyeret aku dalam permainan yang tak akan aku menangkan.
Bukan main org ini! Tega banget dia menghadirkan ancaman padaku. Ternyata benar adagium “tak ada teman yang abadi, kecuali kepentingan”. Orang yang tak suka membaca buku, yang aku tenteng dari kampung, kini terang-terangan menunjukkan taringnya kepadaku. Bah! Aku malah yang takut.
Dia tak peduli aku ini berdarah biru dan punya pengikut loyal yang besar. Lupa juga dia bahwa anak dan menantunya bisa berkuasa di daerah berkat dukungan partaiku. Mukaku yang “cantik” ini mau aku taruh di mana. Bisa jadi sejarah akan mencatat aku kalah pada si ringkih-dungu.
Salah aku adalah underestimate terhadap kemampuannya menghadirkan bahaya kepada siapa saja. Kini dia sangat berkuasa dan nekat. Orang seperti ini tak boleh diremehkan dan tak bisa dihadapi dengan kekuatan seadanya.
Secara mengejutkan dia menyadarkan aku bahwa sesungguhnya aku tak sekuat yang aku pikir. Ternyata sejarah memang berulang. Ayahku dulu juga overestimate atas kekuatannya. Ia merasa tak ada yang bisa menandinginya dalam hal kharisma dan kepintaran.
Bahkan, dia tokoh yang disegani dunia. Faktanya, kekuasaannya dilucuti dengan mudah oleh seorang perwira tak dikenal. Kok, bisa-bisanya aku abai terhadap kasus ayahku, yang sempat membuat kami keluarga yang terbuang dalam waktu sekejap.
Sesungguhnya aku tak mampu memahami bangsaku sendiri. Tak mampu memahami kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang bekerja di negeri ini. Pikiran parokial dan sikap paranoidku terhadao kekuatan-kekuatan riil di luar sana menghilangkan peluangku untuk bisa memainkan peran menentukan dalam perpolitikan bangsa.
Aku juga tak mengambil hikmah dari kegagalanku menjadi presiden di awal reformasi. Padahal, partaiku menang besar dalam pemilu. Yang terpilih malah tokoh dari partai dengab perolehan suara kecil. Aku terlalu meremehkan, bahkan memusuhi kekuatan Islam, yang merupakan anak kandung bangsa ini.
Aku memang kecewa kepada sikap “permusuhan” mereka terhadap ayahku dulu. Tapi sebagai tokoh politik, mestinya aku menganggapnya hal yang wajar dalam persaingan. Toh, tanpa kontribusi mereka tidaj mungkin bangsa ini bisa berdiri secara beradab.
Selama ini aku berpretensi seolah-olah ayahku sendirian yang berjasa bagi tegaknya bangsa yang rumit ini, lupa bahwa sesungguhnya peran tokoh Islam-lah yang mnjd penentu bagi mewujudnya NKRI, bahkan jauh sebelum negara ini merdeka.
Aku juga tak bisa melepaskan diri dari dendamku terhadap partai-partai nasionalis yang pernah menyakiti aku dan partaiku disebabkan hal-hak remeh yang muncul dari persaingan politik kami. Aku terlalu kekanak-kanakan memang.
Aku teringat nasihat teman karibku bahwa aku harus mnjadi negarawan yang melampangkan jiwa, melebarkan hati, dan meluaskan wawasan untuk bisa berdamai dengan semua perbedaan, yang pahit sekalipun. Perbedaan harus dilihat sebagau instrumen untuk mendewasakan bangsa.
“Aneh kalau kau memusuhi Islam, elemen kunci perekat yang menjaga kelangsungan hidup NKRI,” katanya. Tanpa Islam hari ini juga negara ini akan runtuh bagai rumah kartun, tambahnya. Ideologi, mazhab agama, ataupun sikap berbeda dalam memandang suatu isu tidak harus memunculkan kebencian pada pihak lawan. “Ini sikap picik,” katanya lagi.
Tiba-tiba aku kangen padanya. Di mana dia sekarang? Sekiranya aku segera membenahi jiwa dan benakku selepas mendengar nasihatnya, mungkin aku tak mnghadapi masalah sesulit sekarang. Karens alergi dengan beberapa parpol, aku menyempitkan ruang hidup partaiku sendiri.
Akibatnya, si ringkih-dungu mengunci aku dalam ruang yang pengap. Dia menikam aku dari belakang. Et Tu, Joko!? Aku kaget bukan main. Baru kemarin dia menunjukkan sikap budak terhadapku. Sejarang dia mengangkat dirinya tinggi-tinggi bak seorg raja dari zaman kuno. Cis, tak tahu malu!
Jangan-jangan dia sudah membaca buku “The Prince” karya Machiavelli. Kepada penguasa, Machiavelli menasihati agar berlaku curang, abaikan semua moral, dan membuat lawan ketakutan, untuk bisa mempertahankan dan menikmati kekuasaan. Ini yang sedang dia lakukan. Tapi aku juga melakukannya. Bahkan mengkhianati teman.
Ia mnjalankan tipu daya dengan cara halus dan kasar untuk memperpanjang masa jabatannya. Aku tak mau karena dia lebih mendengar menteri utamanya dari pada aku. Mungkin itu awal mula kemarahan dia pdku.
Karena jalan itu aku tutup, dia membujuk dan mengintimidasi parpol-parpol yang mengusung tokoh muda berbakat sebagai bakal capres mereka. Aku tahu tokoh muda itu orang bersih, cerdas, dan independen. Dan dia menolak menjadi keledai si ringkih-dungu. Aku hargai sikapnya yang bermarabat itu.
Demi pilpres yang fair dan legitimated, seharusnya aku membela hak politik tokoh muda itu untuk ikut bersaing dalam pilpres meskipun partaiku tak akan mengusungnya. Toh, dia didukung rakyat. Dan sehrsnya si ringkih-dungu tak ikut cawe-cawe pilpres. Ini menyalahi norma dan konstitusi.
Tapu, ah, semua sudah terlambat. Kita semua akan hancur ramai-ramai, kecuali bila aku keluar dari gua sempit nasionalismeku dan mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara saja.Sayang aku tak mampu melakukannya.
Yang akan aku lakukan hanyalah melawan pengkhianatannya terhadap kepentinganku, keluargaku, dan partaiku. Selebihnya aku berserah diri pada nasib, yang entah ke mana ia akan membawa bangsa ini.
Tangsel, 26 Mei 2023.


![Photo of Kedai Sembako Tak Berpintu dan Pesan di Secarik Kertas itu : Belajar untuk Saling “Menghargai” [Part 56].](https://www.pikiranummat.com/wp-content/uploads/2023/07/B4BEF09D-ADA3-4CD6-B580-D776B6F220D6-390x220.jpeg)



